Pejuang Islam Nikah Mut’ah, atau disebut pula dengan Zuwaj Muaqqat (kawin sementara) atau Zuwaj Munqathi’ (kawin putus) merupakan jenis “pernikahan” yang berbeda dengan perkawinan yang lazim berlaku di masyarakat, utamanya masyarakat Islam. Perkawinan Mut’ah terjadi atas dasar perjanjian bersama antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam waktu tertentu. Jika waktu yang telah ditentukan itu berakhir, maka secara otomatis ikatan perkawinan itu pun berakhir. Kaum Syi’ah itsna ‘Asyariyah dengan berbagail dalih dan alasan memandang perkawinan mut’ah sah menurut syari’at. Rahmat Muthahhari, seorang ulama besar Syi’ah mengatakan nikah mut’ah itu adalah kawin percobaan. Banyak ungkapan tentang nikah mut’ah ini menurut ulama syi’ah, di antaranya “belum sempurna iman seseorang kecuali dengan nikat mut’ah, “dengan seberapa banyak wanita pun nikah mut’ah boleh”, “dengan wanita pelacur boleh”, “dengan perawan tanpa izin orang tuanya boleh, “nikah mut’ah boleh dilakukan dengan siapapun, termasuk dengan majusiyah (musyrikah).” (Kitab Wasail al-Syi’ah, jilid 7, h. 442, 446, 454, 455, 457, 459, 462). Sedangkan kaum Ahlussunnah wal Jama’ah (Sunni) mempunyai dalil-dalil dan alasan untuk meyakini bahwa jenis perkawinan ini tidak sah menurut syari’at. Kaum muslimin di negeri kita, Indonesia, pada umumnya tidak mengenal jenis perkawinan mut’ah. Hal ini disebabkan oleh dua kenyataan: Pertama, hampir semua kaum muslimin di Indonesia bermazhab Ahlussunnah wal Jama’ah, dan dalam fiqih bertaqlid kepada Imam Syafi’i yang mazhabnya terkenal teliti, cermat, hati-hati, dan luwes. Kedua, masyarakat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun yang beragama atau berkepercayaan lain, pantang menerima jenis perkawinan seperti itu. Mereka memandangnya sebagai perkawinan yang tidak sah, tidak beradab, tidak manusiawi, melecehkan harga diri dan kehormatan kaum wanita. Apalagi bila dikaitkan dengan akibat-akibatnya yang dapat merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Maka tak heran, para ulama yang meneliti hukum mut’ah dan dampaknya, misalnya al-Ustadz Abdullah Awadl Abdun, Pengasuh Pesantren Darut Tauhid Malang Jawa Timur, menyamakan nikah mut’ah dengan praktik perzinahan. Setelah meneliti tatacara dan dalih yang digunakan kaum Syi’ah untuk menghalalkan mut’ah, Ustadz Abdullah menyimpulkan ada 15 persamaan nikat mut’ah dengan perzinahan yang diharamkan itu, di antaranya: 1. Mut’ah tanpa saksi, zina tanpa saksi. 2. Mut’ah tanpa wali, zina tanpa wali. 3. Mut’ah dengan sewa dan waktunya sesuai dengan perjanjian, zina juga demikian. 4. Mut’ah telah jelas dilarang oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, zina juga demikian. 5. Orang senang mut’ah suka ganti-ganti wanita, orang yang suka zina juga demikian. 6. Tujuan mut’ah hanya untuk memenuhi hajat seksual, zina juga demikian. 7. Wanita yang dimut’ah selain mengharap upah, juga untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pelacur juga demikian. 8. Orang yang mut’ah tidak berniat membina rumah tangga, pezina juga demikian. 9. Orang yang mut’ah tak ada tujuan memelihara anak, pezina juga demikian. 10. Pemut’ah laki-laki membayar upah, pezina laki-laki juga begitu. 11. Dalam mut’ah tidak ada talaq (perceraian), dalam perzinahan juga demikian. 12. Dalam mut’ah tida ada saling mewarisi, dalam perzinahan juga demikian. 13. Masa nikah mut’ah berakhir dengan habisnya masa kontrak. Perzinahan juga demikian. 14. Wanita pemut’ah menjadi semacam barang dari tangan ke tangan lain. Nasib pezina juga demikian. 15. Anak hasil mut’ah, zina, dan kumpul kebo sama-sama terbengkalai dan tidak akan terurus. Selain berlawanan dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang dianut masyarakat Indonesia, praktik nikah mut’ah juga berlawanan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/tahun 1974. Perkawinan dalam UU tersebut bersifat abadi, sedang nikah mut’ah hanya bersifat sementara. Dalam Pasal 1 undang-undang itu disebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sudah maklum, bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah Sila I (Pertama) dari Pancasila, dan Bab XI pasal 29 ayat (1) dari UUD 1945. Karena itu, nikah mut’ah jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, serta bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 2 dan 3 dijelaskan: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat “mitsaqan ghalidhan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” Bila dilihat lagi pasal-pasal yang ada dalam KHI tersebut, yakni: 1. Pasal 4 dan 8, 2. Bab IV, Bagian Kesatu Pasal 14 (tentang perkawinan), 3. Bagian Ketiga Pasal 19 (tentang wali), 4. Bagian Keempat Pasal 24, 25 dan 26 (tentang saksi), 5. Bagian Kelima Pasal 27 dan 28 (tentang wakil wali) maka kesemunya secara jelas menjelaskan bahwa praktik nikah mut’ah bertentangan dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah mut’ah tersebut bertentangan dengan banyak hal, di antaranya: 1. Bertengan dengan dalil al-Qur’an dan as-Sunnah. 2. Bertentangan dengan ijma’ (konsensus) ulama yang berpendapat tentang keharaman nikah mut’ah. 3. Bertentangan dengan Pancasila, terutama Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila II, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 4. Bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 29 ayat (1). 5. Bertentangan dengan UU No. 1/1974, tentang perkawinan, Pasal 1. 6. Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didinstruksikan oleh pemerintah untuk dilaksanakan (instruksi No. 1 Th. 1991 tanggal 10 Juni 1991). 7. Dari segi sosial dan moral, bertentangan dengan ajaran untuk menjaga kelangsungan perkawinan, kehormatan keluarga, dan kesucian kemaluan. Di lain pihak, bila dikaji langsung pada kitab-kitab rujukan kaum Syi’ah, di antaranya Man La Yahdhuruhu al-Faqih atau Wasail al-Syi’ah, dan sebagainya, akan didapati keterangan bahwa nikah mut’ah bagi mereka adalah salah satu bagian dari keyakinan atau akidah. Disebutkan dalam Man La Yahdhuruhu al-Faqih, jilid 3, halaman 366: “Ibnu Babwaih meriwayatkan dari Ja’far ash-Shadiq: ‘Sungguh mut’ah itu agamaku dan agama leluhurku. Siapa melakukannya, ia telah melakukan agama kami dan siapa mengingkarinya maka ia telah mengingkari agama kami serta ia berakidah dengan selain agama kami.” Dalam Kitab Wasail al-Syi’ah, jilid 7, halaman 442, disebutkan: “Sungguh seorang mukmin tidak sempurna sehingga ia kawin mut’ah.” Berdasarkan keterangan dari rujukan utama mereka ini, nikah mu’ah bagi orang Syi’ah itu adalah suatu hal yang harus dikerjakan, na’udzu billahi mindzalik. Karena itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusannya Nomor: Kep-B-679/MUI/XI/1997, berdasarkan berbagai pertimbangan, telah memutuskan dua hal penting: Pertama, bahwa nikah mut’ah hukumnya haram. Kedua, pelaku nikah mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa harus ada kerjasama antara ulama dan umara’ (pemerintah) dalam memberantas praktik nikah mut’ah oleh kalangan Syi’ah ini. Sudah menjadi rahasia umum, bila aliran ini telah berkembang di bumi Indonesia (lihat beberapa arsip). Di beberapa daerah, praktik mut’ah juga telah menimbulkan keresahan masyarakat. Dikhawatirkan bila tidak ada kebijakan tegas dari aparat pemerintah, baik secara preventif maupun tindakan langsung, hal ini dapat memicu kericuhan dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Idealnya, memang terdapat job discription yang jelas antara juru dakwah, pelaku amar ma`ruf nahi munkar, dan pemerintah. Bila para juru dakwah, pelaku amar ma\`ruf nahi munkar, dan pemerintah, dapat menjalankan wewenang sesuai porsinya, maka kondisi ini insya Allah akan dapat menghindarkan keresahan dan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Berangkat dari pemahaman di atas, dan sebagai bentuk kerjasama dan sinergi antara ulama dan umara’ (pemerintah), dalam rangka menghindarkan masyarakat Sulawesi Selatan dari bahaya praktik mut’ah, maka kami memandang perlu diadakannya seminar terkait hal tersebut di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, sebagai titik tolak langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil oleh pihak kepolisian dan ulama.
Kalimat Verbal Masa Sekarang dalam Amiyah Arab Saudi
5 minggu yang lalu






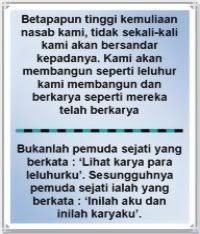










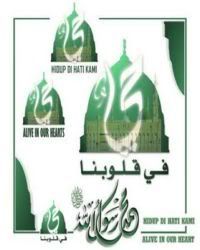







0 komentar:
Posting Komentar